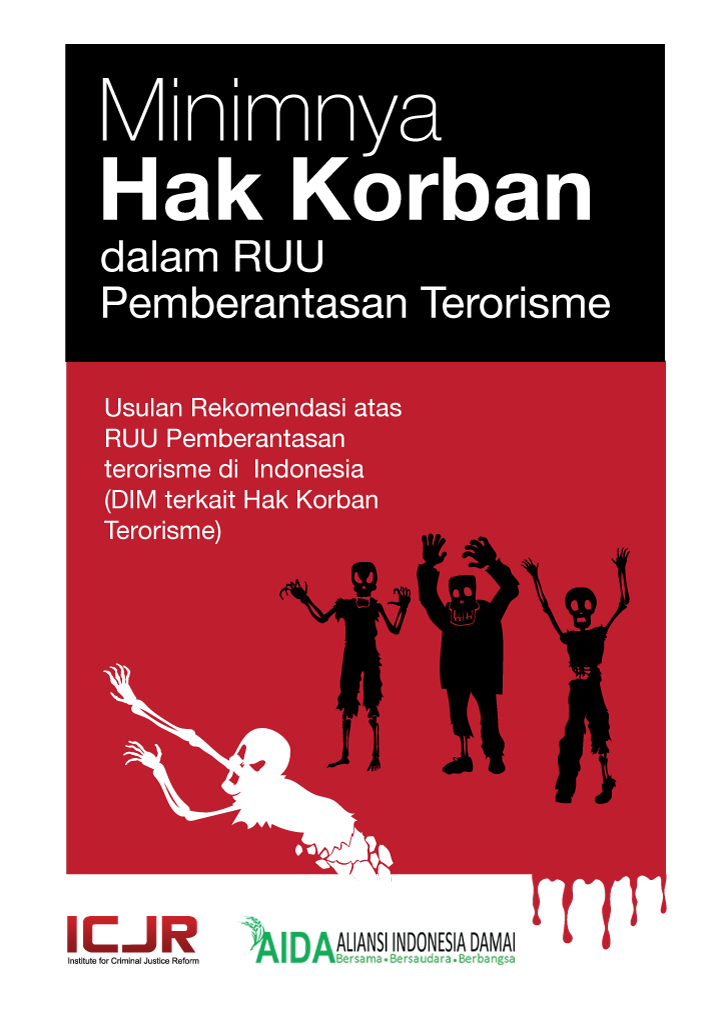Dalam perbincangan terorisme yang muncul ke publik, isu korban nyaris terabaikan. Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan, perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (offender oriented) ketimbang korban (victim oriented). Padahal korban merupakan subyek yang paling terzalimi akibat kesadisan aksi terorisme.
Besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan korban tampaknya merembet ke pemangku ororitas (pemerintah). Indikatornya, titik tekan dalam naskah revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang diajukan pemerintah ke DPR RI adalah kewenangan aparat hukum dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Bab VI UU No. 15 Tahun 2003 yang membahas soal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban terorisme tak tersentuh revisi sama sekali. Seolah-olah tak ada masalah dalam lima pasal (36-42) yang menjelaskan hak-hak korban tersebut.
Padahal, sebagai contoh kasus, mengutip data Yayasan Penyintas Indonesia (wadah korban terorisme di Indonesia), dari total 544 korban terorisme di Indonesia yang tercatat, baik korban meninggal, cacat permanen, luka berat dan ringan, belum ada satu pun yang mendapatkan kompensasi dari negara. Kompensasi adalah hak korban yang secara gamblang dan detail diatur dalam pasal 36, 38, 39, 40, 41, dan 42 UU No. 15 Tahun 2003. Namun hingga kini negara belum melaksanakan hak tersebut karena terkendala oleh rumitnya prosedur hukum.
Kompensasi dan hak-hak korban lainnya, seperti rehabilitasi medis dan psikis, serta bantuan psikososial kepada korban terorisme, merupakan kewajiban negara akibat kelalaiannya dalam melindungi keamanan fisik warganya. Korban terorisme adalah orang-orang yang “mengorbankan diri” secara sukarela atas nama negara. Karena hampir selalu ada koneksi baik motivasi langsung atau tidak langsung antara tindakan terorisme dan kebijakan negara.
Kompensasi adalah salah satu masalah pokok terkait hak korban yang mestinya dikaji ulang. Hal lain yang sangat penting namun belum termaktub dalam UU No. 15 Tahun 2003 adalah garansi negara untuk membiayai perawatan medis korban sejak masa kritis hingga sembuh total. Dalam kasus Teror Thamrin 2016, penanggung jawab pembiayaan penanganan rehabilitasi medis bagi korban tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa instansi/lembaga yang menyatakan akan menanggung biaya yang timbul, namun dalam praktiknya, hingga pertengahan Februari 2016, beberapa rumah sakit yang merawat korban belum mendapat kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut.
Poin lain yang tak kalah penting dalam revisi UU tersebut adalah memasukkan definisi korban terorisme. Ironisnya, meski ada bab khusus yang mengatur hak-hak korban (langsung maupun sekunder), namun pengertian ‘korban’ tak termaktub dalam ketentuan umum (pasal 1). Karena saat ini Rancangan revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sedang dibahas di DPR RI. Maka paper ini memaparkan argumentasi legal dan faktual terkait pentingnya keberpihakan pada korban terorisme.
Unduh Disini